oleh Franz Kafka
*Diterjemahkan oleh Janoary M Wibowo
Ketika itu minggu pagi yang indah di suatu musim semi. George Bendermann, pedagang muda, duduk di ruangan pribadinya di lantai pertama salah satu rumah di bangunan kumuh yang berjajar di tepi sungai, yang kesemua rumah itu hampir tak dapat dibedakan satu sama lain kecuali oleh tinggi atap dan warnanya. Dia baru saja rampung menuliskan sebuah surat untuk temannya yang kini berada di luar negeri, baru saja menyegel surat itu dengan sikap sekenanya dan seenaknya, lalu dengan siku menopang dia memandang keluar jendela, ke sungai, ke jembatan, ke bukit hijau yang indah di seberang sungai.
Dia berpikir tentang seorang teman, yang merasa tidak puas dengan kondisi kampung halaman, lalu melarikan diri ke Rusia beberapa tahun sebelumnya. Sekarang teman itu menjalankan usahanya di St. Petersburg, yang pada mulanya berjalan begitu lancar tapi setelah sekian lama kini usahanya itu mengalami kemunduran, dia mengeluhkan menurunnya jumlah pengunjung. Maka dia menyibukkan diri dengan bekerja serabutan di tanah asing. Jenggot tebal itu hanya mampu menyembunyikan muka murung dari muka yang George kenal sejak kanak-kanak, dan kulit yang menguning seperti menunjukkan penyakit yang makin parah. Seperti yang dia ceritakan melalui surat-suratnya, dia tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan koloni senegaranya di tempat itu, dan juga jarang berinteraksi dengan penduduk lokal, serta memutuskan untuk selamanya melajang.
Apa yang mesti dituliskan seseorang kepada laki-laki yang jelas-jelas sudah kehilangan arah, seseorang itu bisa menuliskan rasa turut berduka cita tapi tetap tak bisa menolong. Haruskah seseorang itu menasihatinya agar pulang, menjalani hidup lamanya, menjalin kembali semua hubungan pertemanan lama—yang memang sudah semestinya dikatakan, dan sembari meminta pertolongan kepada teman-teman itu? Tapi di saat bersamaan, seseorang itu juga ingin mengatakan seperti kebanyakan orang—makin ramah cara mengatakannya akan makin membuat laki-laki itu terluka—bahwa usaha yang dilakukan lelaki itu sudah gagal, dan dia mestinya merelakan semua dengan pulang ke kampung halaman, membiarkan dirinya dianggap sebagai bocah pemboros yang akhirnya kembali. Barangkali tidak seorang pun akan mengerti penderitaannya, sebab di mata mereka, kini dia hanyalah bocah tua yang butuh pertolongan dari teman-teman kaya yang lebih memilih bertahan di kampung halaman. Lalu, bagaimana seseorang bisa tega mengutarakan benar maksudnya mengingat seluruh penderitaan yang dia alami? Dan dengan begitu, akan sulit juga membujuknya pulang. Dia terang-terangan mengatakan tentang dirinya yang sudah tidak mengenal lagi kondisi kampung halamannya, memutuskan untuk bertahan di tanah asing, selain karena nasihat-nasihat pahit yang dikatakan teman-temannya, yang kerap membuatnya merasa diasingkan. Namun, jika dia benar-benar menuruti nasihat-nasihat itu, dia akan tertekan di sini. Keadaan tidak mendukungnya untuk bisa bertahan hidup, baik bersama teman atau tanpa teman. Dia akan malu mengetahui dirinya benar-benar tak punya tempat pulang, bukankah hal itu berarti dia lebih baik tetap bertahan di sana, seperti yang dia putuskan? Dengan pertimbangan seperti itu, seseorang itu berpikir, jika dia meminta temannya pulang, dia hanya akan memperburuk nasib temannya di sini.
Dengan pertimbangan itu pula, karena seseorang itu ingin menjaga hubungan dengan bersurat-suratan, dia pikir tak perlu mengirimkan kabar yang sebenarnya yang bisa merusak kedekatan di antara mereka. Hal semacam itu berlangsung lebih dari tiga tahun sejak teman itu pergi dari rumah. Seseorang itu menceritakan hal-hal yang dibuat-buat, tentang kondisi politik di Rusia yang tidak mengijinkan pengusaha kecil keluar dari sana, meski di samping itu, orang-orang Rusia tetap bisa berpergian ke mana saja. Dan itulah tiga tahun yang mengubah George. Sejak ibunya meninggal, kurang lebih dua tahun sebelumnya, George tinggal serumah, berbagi atap dengan ayahnya yang renta. Temannya mengetahui hal itu, dan beberapa kali menyatakan rasa simpati datar melalui surat-suratnya. Bagi temannya, kesedihan yang diceritakan George benar-benar tidak dapat dibayangkan terjadi di negeri asing. Ketika itu George mengambil alih semuanya termasuk urusan perusahaan dengan ambisi dan tekad yang kuat. Barangkali jika ibunya masih hidup, ayahnya tak akan membiarkan keinginan George mengambil alih dan mengembangkan usaha dengan caranya sendiri. Barangkali karena, sejak ibunya meninggal, ayahnya menjadi lebih ceroboh dalam menangani perusahaannya. Barangkali keberuntungan memegang peran yang lebih besar—sesuatu yang mungkin sekali terjadi, karena selama dua tahun itu, perusahaan mereka mengalami peningkatan pesat. Mereka menambah jumlah karyawan dua kali lipat, perputaran uang menjadi lima kali lipat, dan tidak menutup kemungkinan usaha mereka akan terus berkembang di masa yang akan datang.
Temannya, bagaimanapun juga, tidak perlu mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Sebelumnya, barangkali di surat pernyataan bela sungkawa yang terakhir, dia menyarankan George untuk pindah ke Rusia, mengembangkan usaha bermodalkan pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan perusahaan. Hal itu bisa menguntungkan George jika melihat bagaimana perusahaan George kini. Tapi George tidak ingin menulis surat yang berkisah tentang kesuksesan. Dan jika George menuliskan hal itu sekarang, semua terkesan terlambat dan aneh.
Jadi, George memutuskan untuk menulis kepada temannya itu hal-hal yang remeh temeh, barangkali seperti tumpukan kenangan yang muncul ketika seseorang memandangi langit sore di hari minggu yang tenang. Yang dia inginkan adalah tidak merusak gambaran-gambaran diciptakan temannya tentang kota yang lama ditinggalkan, yang barangkali sedang temannya pertimbangkan untuk ditinggali kembali. Maka terjadilah, ketika George menceritakan tiga kali dalam sebuah surat panjang tentang pertunangan antara seorang laki-laki biasa dan perempuan biasa. Dan tidak seperti yang George bayangkan, temannya itu malah penasaran dan tertarik mendengar cerita itu.
George lebih suka menulis kepada temannya kisah itu, daripada mengakui bahwa sebulan lalu dia lah yang bertunangan dengan gadis dari keluarga kaya, Frieda Brandenfeld. George kerap bercerita kepada tunangannya tentang seorang teman dan hubungan yang mereka lakukan dengan bersurat-suratan. “Tak mungkin baginya untuk datang ke pernikahan kita?” tanya gadis itu, “tapi aku punya hak untuk bertemu dengan semua temanmu.” “Aku tidak ingin membuatnya sedih,” George menjawab. “Jangan salah paham. Dia mungkin datang, paling tidak begitulah yang aku harapkan, tapi dia barangkali datang dengan terpaksa, dan merasa terluka, dan iri kepadaku. Dia tentu merasa sedih, apalagi sekarang dia belum mampu mengatasi rasa sedih kembali ke kampung halaman sendiri. Sendiri, bisakah kau mengerti keadaannya?” “Ya, tapi apakah dia tidak bisa memandang pernikahan kita dari sisi lain?” “Bisa saja, tapi aku tidak bisa menjamin hal itu. Bagaimana pun juga, cara pandangnya tidak seperti yang kaubayangkan.” “Jika kau punya teman seperti itu, semestinya kau tidak usah bertunangan saja.” Beberapa saat kemudian, gadis itu, dengan napas tersengal setelah berciuman, mendesak lagi, “Meski begitu, aku tetap merasa kecewa.” Lalu George mulai berpikir untuk mengatakan semua ini sejujur-jujurnya, dia pikir temannya tidak akan merasa terluka. “Memang begitulah aku, dan semestinya begitulah cara dia menerimaku,” pikir George. “Aku tidak perlu menjadi orang lain agar dia merasa nyaman menjalin pertemanan denganku.”
Dan, akhirnya, dia benar-benar mengatakan kepada temannya perihal pertunangan, dalam sebuah surat panjang yang dia tulis di Minggu pagi itu, beginilah kata-katanya, “Berita terbaik disimpan untuk penutup. Aku sudah bertunangan dengan Frieda Bradenfeld, seorang gadis dari keluarga berkecukupan, yang baru datang ke kota ini lama setelah kepergianmu dan mungkin kamu tidak mengenal mereka. Kuharap ada kesempatan lain untuk menceritakan kepadamu tentang tunanganku. Hari ini, kupikir cukup dengan memberitahukan kepadamu bahwa aku sangat merasa beruntung dengan pertunangan ini, dan apabila kau merasa khawatir dengan pertemanan kita ini, satu-satunya yang berubah di antara kita adalah kita akan mempunyai, bukan hanya seorang kawan biasa, melainkan seorang kawan perempuan yang bahagia. Terlebih lagi, tunanganku, yang menitipkan salam hangatnya untukmu, akan segera menulis suratnya sendiri untukmu. Kau akan mendapat seorang teman perempuan yang ramah, sesuatu yang tidak serta-merta mengganggu status lajangmu. Aku tahu ada banyak hal yang menghalangimu untuk pulang dan mengunjungi kami, akan tetapi, bukankah pernikahanku adalah kesempatan yang tepat untuk meruntuhkan tembok penghalang itu? Tapi bagaimana pun juga, lakukanlah apa-apa yang menurutmu baik, tanpa membuat dirimu sendiri tidak nyaman.”
George duduk cukup lama di depan meja tulis dengan surat itu di tangannya, kepalanya menengok ke arah jendela. Dia terhenyak, lalu tersenyum kosong yang dipaksakan ketika menyadari seorang tetangga yang melintas menyapanya dari luar jendela.
Akhirnya dia melipat surat itu dan memasukkannya ke kantong lalu berjalan keluar ruangan, menyusuri lorong kecil menuju ke ruangan ayahnya, yang sudah tidak dia kunjungi selama berbulan-bulan. Tak ada alasan untuk melakukannya, karena dia selalu bertemu dengan ayahnya di tempat kerja dan selalu menikmati makan siang mereka di restoran yang sama. Di sore hari, tentu saja, mereka berdua melakukan urusan masing-masing. Meski seringkali, kecuali saat George dikunjungi temannya, atau sekarang dikunjungi tunangannya, mereka masih melewati sore duduk bersama di ruang tengah, dengan koran masing-masing menutupi wajah mereka.
George terkejut betapa gelapnya kamar ayahnya, bahkan di pagi yang cerah seperti itu. Semacam bayangan yang memanjang dari dinding tinggi yang berada di sisi sungai yang menyebabkan kegelapan itu. Ayahnya sedang duduk membaca koran di dekat jendela di sebuah sudut ruangan yang dihiasi bermacam-macam benda yang mengingatkan pada kesedihan akan kematian ibunya. Koran itu dipegang sedemikian rupa untuk menyesuaikan kemampuan melihatnya yang sudah melemah. Di meja, terlihat makanan untuk sarapan, yang sepertinya belum dia makan sama sekali.
“Ah, George,” kata ayahnya, berdiri dan berjalan ke arah George. Piyama tidurnya yang tidak ditalikan menggantung dan bergerak-gerak seiring dia berjalan. “Ayahku masih seperti raksasa,” pikir George.
Lalu George berkata, “Gelap sekali ruangan ini.”
“Ya, tentu saja gelap,” ayahnya menjawab.
“Dan kau malah menutup jendela?”
“Aku lebih nyaman seperti itu.”
“Padahal di luar cukup hangat,” kata George, seperti hendak mengatakan hal lain, lalu duduk.
Ayahnya membereskan piring tempat sarapan dan meletakkan di lemari makan.
“Aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu,” George melanjutkan, yang diikuti gerakan berjalan yang tanpa daya orang tua itu, “Aku ingin mengirimkan berita tentang pertunanganku ke St. Petersburg.” George sedikit menarik surat dari sakunya tapi segera memasukkannya kembali.
“Ke St. Petersburg?” ayahnya bertanya.
“Kepada temanku,” kata George, mencoba memandang mata ayahnya, “Ayahnya jauh berbeda dengan yang kerap kulihat di tempat kerja,” pikir George. “Sekarang, betapa tegapnya dia duduk dengan tangan terlipat di dada.”
“Oh iya, kepada temanmu,” kata ayahnya, dengan penekanan.
“Begitulah, Yah. Pada mulanya aku ingin menyembunyikan pertunangan ini darinya. Tanpa pertimbangan dan alasan apapun. Tapi kau tahu sendiri, dia orang yang rumit. Aku pikir dia akan bisa memahami pertunanganku ini dan memaafkanku, bahkan jika cara hidupnya yang soliter itu akan membuat semua ini makin sulit, aku tidak peduli, mestinya dia tidak menganggap semua ini masalah personal.”
“Dan sekarang kau memikirkan hal ini dari sudut pandang lain?” tanya ayahnya. Dia menata koran di ambang jendela, dan meletakkan kacamata baca di atasnya.
“Ya, sekarang aku mulai mempertimbangkannya. Jika dia teman baikku, maka aku pikir pertunanganku yang bahagia akan membahagiakannya juga. Itulah mengapa aku tak lagi ragu mengabarkan kepadanya. Tapi sebelum aku mengirim surat kepadanya, aku ingin mengatakan niatku ini kepadamu.”
“George,” kata ayahnya, mulutnya yang tanpa gigi terbuka, “Dengarkan aku! Kau datang kepadaku dengan semua ini, membincangkan semua ini. Tidak ada keraguan bagiku bahwa itu kebanggaan tersendiri. Tapi, itu tidak berarti apa-apa. Lebih parah lagi, jika ternyata kau tidak mengatakan seluruhnya kepadaku. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Sejak kematian ibumu, beberapa hal berjalan tidak semestinya di sini. Barangkali saat-saat untuk membincangkan itu sudah datang, lebih cepat dari yang kita kira. Dalam urusan perusahaan, penjualan yang bagus membuatku tenang. Barangkali tidak ada yang sedang kausembunyikan dariku, sekarang aku tidak menganggap ada yang sedang kaulakukan di belakangku. Aku tidak sekuat dulu, ingatanku sudah menurun, aku tidak bisa jeli dalam melihat segala sesuatu sekarang ini. Pertama-tama, yang terjadi biarlah terjadi, lalu kematian ibumu berimbas lebih parah kepadaku daripada kepadamu. Dan karena kita membahas suratmu itu, aku mohon, George. Jangan memperdaya aku. Ini masalah sepele, tak perlu membahasnya panjang lebar, tapi jangan membohongiku. Apakah kau benar-benar punya teman di St. Petersburg?”
George tertegun malu, “Mari kita lupakan tentang temanku. Bagiku, ribuan teman tetap tak bisa menggantikan seorang ayah. Kau tahu apa yang kupikirkan? Kau tidak serius merawat dirimu sendiri. Tapi usia tetaplah usia. Kau tak tergantikan di perusahaan itu, dan kau sadar benar akan hal itu. Tapi jika urusan perusahaan mulai mengancam kesehatanmu, aku bersumpah, aku akan menutupnya esok hari. Tapi itu tak akan terjadi. Kita harus membicarakan hidupmu dengan cara lain, yang benar-benar berbeda. Di sini, kau duduk dalam gelap saat ruang tengah begitu terang benderang. Kau makan sedikit padahal kau mesti menjaga kesehatanmu. Kau duduk di dekat jendela yang tertutup, padahal udara segar akan membuatmu lebih baik. Tidak seperti itu, Yah. Aku akan membawamu ke dokter, dan kita akan mengikuti anjurannya. Kita akan bertukar ruangan. Kau pindah ke ruangan depan, aku akan menempati ruangan ini. Untukmu, tidak akan ada perubahan. Semua perabotan akan ikut dipindah. Tapi masih ada waktu untuk semua itu, sekarang, aku akan mengantarmu ke ranjang. Kau butuh banyak istirahat. Mari, kubantu kau mengganti pakaianmu. Kau akan lihat, aku bisa melakukannya untukmu. Atau kau ingin pindah ke ruang depan sekarang juga, kau bisa beristirahat di ranjangku. Aku bersedia melakukannya jika kau ingin.”
George berdiri di samping ayahnya, membiarkan rambut putih ayahnya yang acak-acakan terbenam di dadanya.
“George,” kata ayahnya pelan, tanpa bergerak.
George segera berlutut di samping ayahnya. Dia melihat bola mata yang besar di wajah yang lelah ayahnya menatap langsung ke matanya.
“Kau tidak punya teman di St. Petersburg. Selama ini kau terlalu sering membual, dan ketika kau berbicara padaku, kau bahkan tidak bisa mengendalikan sifat burukmu yang satu itu. Jadi bagaimana bisa kau punya teman di sana, aku tidak percaya itu.”
“Berusahalah mengingatnya, Yah,” kata George. Dia mendukung ayahnya dari kursi, dan ketika ayahnya berdiri begitu lemahnya, piyamanya hampir jatuh terlepas. “Sudah hampir tiga tahun sejak temanku itu mengunjungi kita. Aku masih ingat benar ketika kau tidak menghiraukan dia, bahkan ketika dia sedang duduk di ruanganku. Aku bisa mengerti keenggananmu bertemu dengannya. Temanku itu memang terkesan aneh. Tapi kau bahkan sudah berbincang dengannya. Saat itu, aku merasa senang ketika mendapati kau mendengarkan dia, menganggukkan kepalamu, dan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika kau mau mengingatnya, kau mungkin akan ingat. Seperti ketika dia bercerita kepada kita kisah mengagumkan tentang Revolusi Rusia. Misal, ketika dia sedang melakukan perjalanan kerja ke Kiev, di tengah kekacauan di sana, dia melihat pendeta di sebuah balkon menyayatkan tanda salib di telapak tangannya, lalu mengangkat tangan berdarah itu, lalu berteriak-teriak ke kerumunan. Kau bahkan kerap mengulang-ulang cerita itu sampai sekarang.”
Sementara itu, George berhasil membantu ayahnya duduk kembali dan dengan hati-hati melepaskan piyama, yang dia pakai di atas pakaian dalam linen, lalu George melepaskan kaos kaki ayahnya. Melihat seluruh pakaian yang sudah tanggal, yang nampak jelas tidak lagi bersih, George mendesah pada dirinya sendiri bahwa dia sudah menelantarkan ayahnya. Sudah tentu menjadi tanggung jawabnya untuk mengurusi pakaian kotor ayahnya. George belum membicarakan secara terang-terangan kepada tunangannya tentang bagaimana rencananya untuk masa depan ayahnya, karena mereka beranggapan bahwa ayahnya akan memilih hidup sendirian di apartemen tua itu. Namun sekarang dia sudah bulat tekad untuk mengajak ayahnya hidup bersama istrinya nanti. Jika dilihat lebih seksama, sepertinya perhatian yang George sediakan untuk ayahnya sedikit terlambat.
George memapah ayahnya menuju ranjang. Dia mengalami perasaan yang mengerikan ketika dia menyadari, beberapa langkah menuju ranjang, ayahnya melepaskan tangannya dari tangan George hanya untuk memainkan rantai jam yang menggantung di dadanya. George tidak langsung bisa merebahkan ayahnya ke ranjang, dia dengan sikap memegang ayahnya, yang tangannya masih saja memainkan rantai jam.
Segera setelah berhasil merebahkan ayahnya ke ranjang, semua nampak melegakan. George menyelimuti ayahnya, menarik selimut itu bahkan terlalu tinggi, hingga menutupi bahu ayahnya. Ayahnya melihat George dengan pandangan yang tidak menyenangkan.
“Kau masih ingat dia, bukan?” George memberanikan diri bertanya.
“Apa kau sudah benar-benar menutupiku dengan selimut?” tanya ayahnya, memastikan bahwa ujung kakinya benar-benar sudah masuk ke selimut.
“Tidurlah dengan nyaman,” kata George sembari menata ranjang ayahnya agar lebih nyaman lagi.
“Apa kau sudah menutupiku?” Ayahnya bertanya sekali lagi, seperti memaksa George menjawab.
“Tidurlah, selimutnya sudah benar.”
“Tidak!” teriak Ayahnya, memotong jawaban George. Dia melemparkan selimut itu dengan kuatnya sampai melayang, lalu dia berdiri di ranjangnya. Dia menegapkan dirinya dengan satu tangannya yang menyentuh atap. “Kau ingin menutupiku dengan selimut, aku tahu itu, anakku. Tapi aku belum kaututupi dengan kebenaran. Jika ini adalah sisa-sisa tenaga terakhirku, sepertinya pantas kucurahkan kepadamu, bahkan terlalu pantas untukmu. Ya, aku tahu temanmu. Dia sudah kuanggap anak sendiri. Dan karena itulah kau mengkhianatinya bertahun-tahun. Kau pikir selama ini aku tidak menangis untuknya? Itulah alasan mengapa kau mengurung diri di kantor, tidak ada yang boleh mengganggumu, bos sedang sibul. Itulah mengapa kau menuliskan surat-suratmu yang bermuka dua ke Rusia. Tapi sayang sekali, tidak ada yang perlu mengajari seorang ayah untuk mengetahui tingkah polah anaknya. Dan sekarang, ketika kau pikir kau sudah mengelabuinya, kau meletakkan bokongmu di dadanya hingga kaupikir dia tidak bisa bergerak, lalu setelah seperti itu, anakku dengan sikap lelaki sejati mengatakan keputusannya untuk menikah.”
George menatap gemetar ke arah ayahnya. Bayangan temannya di St. Petersburg, yang tiba-tiba dikenal ayahnya sangat baik, tiba-tiba memenuhi kepalanya melebihi biasanya. Dia melihat ekspansinya ke Rusia runtuh. Dia melihat dirinya di ambang pintu menuju kekosongan, kemajuan bisnisnya terampas, berdiri di antara rongsokan, dagangan yang berkeping-keping, tabung gas yang bergelimapangan, hanya berdiri. Mengapa bisa sampai seperti ini!
“Lihatlah aku,” teriak ayahnya, dan George bergegas sadar, terperanjat.
“Karena perempuan itu menaikkan roknya,” ayahnya memulai dengan nada geram, “karena perempuan itu menaikkan roknya seperti ini, angsa menjijikkan,” memeragakan yang dia katakan dengan mengangkat celana pendeknya sedemikian tinggi hingga luka-luka perang di pahanya nampak, “karena perempuan itu menaikkan roknya seperti ini dan seperti itu, kau mulai mengajaknya berbincang, dan beginilah caramu bermesra-mesraan dengannya tanpa merasa terganggu, kau mempermalukan kenangan ibumu, mengkhianati temanmu, dan merebahkan ayahmu di ranjang agar dia tidak bergerak. Tapi dia bisa bergerak, bukan?”
Dan ayah George berdiri tanpa berpegangan, menendangkan kakinya ke arah George. Air mukanya berseri-seri seperti baru saja mendapatkan pencerahan.
George berdiri di pojok kamar, sejauh mungkin dari ayahnya. Sekian lama di sana memutuskan untuk mengamati semua dengan seksama, takut apabila ada serangan mendadak dari atas atau samping yang mengagetkannya. teringat alasan awalnya datang ke ruangan ini, dan mati-matian berusaha melupakannya, seperti berusaha memasukkan benang pendek ke lubang jarum.
“Tapi sekarang temanmu tidak benar-benar dikhianati,” teriak ayahnya, telunjuknya bergerak maju mundur, menekankan maksud perkataannya. “Aku menjadi matanya di sini.”
“Dasar pelawak!” George tidak tahan lagi untuk tidak berkata-kata. Lalu segera menyadari betapa perkataannya memperburuk keadaan dan dia menahan lagi lidahnya. Tapi terlambat, matanya beku, kepedihannya kembali dua kali lipat.
“Ya, memang aku sedang bermain lawakan. Drama. Betapa dunia yang indah. Apalagi penghiburan yang tersisa bagi seorang duda tua sepertiku? Katakan padaku, dan sambil kau menjawabnya, anakku tersayang, apalagi yang tersisa di ruang kerjaku, dipermainkan oleh karyawan yang tidak setia, menjadi renta jiwa dan raga? Dan anakku melenggang bebas mengangkangi dunia, menunggangi perusahaan yang sudah lama aku rintis, menerima semua pujian dengan bangga, dan menelantarkan ayahnya dengan bibir terkatup dan tersenyum layaknya lelaki sejati yang terhormat. Kau pikir aku tidak mencintaimu, aku, seseorang yang membuatmu bisa hidup?”
“Sekarang dia akan terjatuh ke depan,” pikir George. “Bagaimana jika dia terjatuh dan terkapar.” Kata-kata itu berdenging di kepalanya.
Tubuh ayahnya condong ke depan, tapi dia tidak terjatuh. Saat George tidak bergerak mendekat, seperti yang dia harapkan, dia menegakkan lagi tubuhnya.
“Tetaplah di tempatmu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Kau pikir kau masih punya cukup kekuatan untuk memberanikan dirimu sendiri menghampiriku seperti dugaanmu? Bagaimana jika kau salah? Aku masih jauh lebih kuat dari kau. Barangkali apabila aku sendirian, aku sudah akan mundur, tapi ibumu memberikan aku kekuatan untuk bertahan, seperti ketika dia mendorongku untuk menjalin pertemanan dengan temanmu. Dan, aku punya ‘teman’ untukmu di sakuku.”
“Dia bahkan tidak memiliki saku di celana pendeknya.” pikir George, dan seketika itu juga berpikir bahwa ayahnya adalah orang paling konyol sedunia. Pikiran itu hanya selintas saja, sebab di kepalanya pikiran-pikiran lain masih sibuk berlintasan.
“Maka rengkuhlah tangan tunanganmu dan langkahi mayatku. Dan aku akan menghantui hubungan kalian, dan kau tidak akan bisa berbuat apa-apa.”
George menyeringai, dia tidak percaya perkataan ayahnya. Sang ayah mengangguk ke arah sudut di mana George berdiri, menekankan maksud dari perkataannya.
“Sungguh kau membuatku geli hari ini ketika kau datang dan bertanya apakah kau mesti menulis kepada temanmu tentang pertunanganmu. Padahal dia sudah tahu semuanya, bocah dungu, dia sudah tahu semuanya! Aku sudah menulis surat kepadanya, kau lupa mengambil peralatan menulisku. Itulah mengapa dia tidak pernah berkunjung bertahun-tahun, sebab dia sudah tahu ratusan kali dari yang kau tahu. Tangan kirinya meremas suratmu yang tidak pernah dia baca, sedangkan tangan kanannya memegang suratku, ia membacanya.”
Dengan antusias, ayah George mengayunkan tangannya sembari berteriak, “Dia tahu semua ribuan kali lebih banyak.”
“Sepuluh ribu kali!” kata George, perkataannya dimaksudkan untuk mengejek ayahnya, tapi nada bicaranya mengatakan maksudnya lebih jujur dengan bergetar ketakutan.
“Sudah bertahun-tahun aku mengawasimu jika sewaktu-waktu kau akan datang dengan pertanyaan semacam ini. Kau pikir aku peduli dengan hal lain? Kau pikir aku membaca koran? Lihat!” ayahnya melemparkan koran yang entah bagaimana sudah dia bawa ke ranjang ke arah George, sebuah koran lama, yang selama ini tidak pernah diperhatikan George.
“Berapa lama lagi agar kau bisa bersikap dewasa? Ibumu meninggal. Dia tidak bisa menikmati masa-masa yang menyenangkan. Temanmu merana di Rusia, tiga tahun lalu dia sudah cukup merana untuk dibuang, dan seperti keadaanku, kau mengulangi perbuatanmu kepadaku. Kau benar-benar berbakat untuk itu!”
“Jadi selama ini kau berbohong kepadaku,” teriak George.
Dengan nada yang meremehkan, ayahnya berkata dengan tenang dan tegas, “Kiranya kau mengatakan hal semacam itu sejak dulu. Sekarang, perkataanmu terdengar tidak masuk akal.”
Dan dengan suara yang lebih lantang, “Jadi sekarang kau tahu ada dunia di luar dirimu sendiri. Sampai sekarang yang kau pikir hanya dirimu sendiri. Di dalam dirimu, kau hanyalah bocah lugu, tapi lebih dalam lagi, kau adalah manusia yang jahanam! Dan oleh karena itu, camkan ini: kukutuk kau mati tenggelam!”
George merasa dirinya diburu sesuatu dari ruangan ayahnya. Suara tubuh ayahnya yang jatuh menghempas ranjang dan perkataan ayahnya masih terus mengiang di telinganya. Dia serampangan berlari turun, seperti pesawat yang sedang menukik, mengejutkan pembantu rumah tangga yang datang setiap pagi untuk membersihkan rumah. “Ya, Tuhan!” perempuan itu tersentak, melindungi mukanya dengan kedua tangan. Tapi George tidak memedulikannya, dia melompat ke arah pintu, menggeloyor menyeberang jalanan ke arah sungai. Tangannya memegang erat pagar jembatan seperti seorang laki-laki kelaparan menggenggam makanannya. Lalu dia meloncat, seperti gerakan senam yang mengagumkan yang pernah dilakukan di masa mudanya, yang kala itu membuat orang tuanya bangga. Dia masih berpegangan pada pagar, genggamannya melemah, seketika itu dia melihat rombongan motor melintas yang suaranya akan dengan mudah menenggelamkan suara jatuhnya. Dia berbisik lirih, “Ayah, Ibu, aku selalu mencintai kalian bagaimanapun juga,” dan melepaskan genggamannya.
Pada saat itu, ada yang mengalir begitu derasnya melewati jembatan.
nb : diterjemahkan bebas oleh JMW, dari cerpen The Judgement karya Franz Kafka.
Sumber: Facebook Membaca Karya Franz Kafka
http://www.facebook.com/home.php?ref=tn_tnmn#!/groups/252713648090123/
*Diterjemahkan oleh Janoary M Wibowo
Ketika itu minggu pagi yang indah di suatu musim semi. George Bendermann, pedagang muda, duduk di ruangan pribadinya di lantai pertama salah satu rumah di bangunan kumuh yang berjajar di tepi sungai, yang kesemua rumah itu hampir tak dapat dibedakan satu sama lain kecuali oleh tinggi atap dan warnanya. Dia baru saja rampung menuliskan sebuah surat untuk temannya yang kini berada di luar negeri, baru saja menyegel surat itu dengan sikap sekenanya dan seenaknya, lalu dengan siku menopang dia memandang keluar jendela, ke sungai, ke jembatan, ke bukit hijau yang indah di seberang sungai.
Dia berpikir tentang seorang teman, yang merasa tidak puas dengan kondisi kampung halaman, lalu melarikan diri ke Rusia beberapa tahun sebelumnya. Sekarang teman itu menjalankan usahanya di St. Petersburg, yang pada mulanya berjalan begitu lancar tapi setelah sekian lama kini usahanya itu mengalami kemunduran, dia mengeluhkan menurunnya jumlah pengunjung. Maka dia menyibukkan diri dengan bekerja serabutan di tanah asing. Jenggot tebal itu hanya mampu menyembunyikan muka murung dari muka yang George kenal sejak kanak-kanak, dan kulit yang menguning seperti menunjukkan penyakit yang makin parah. Seperti yang dia ceritakan melalui surat-suratnya, dia tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan koloni senegaranya di tempat itu, dan juga jarang berinteraksi dengan penduduk lokal, serta memutuskan untuk selamanya melajang.
Apa yang mesti dituliskan seseorang kepada laki-laki yang jelas-jelas sudah kehilangan arah, seseorang itu bisa menuliskan rasa turut berduka cita tapi tetap tak bisa menolong. Haruskah seseorang itu menasihatinya agar pulang, menjalani hidup lamanya, menjalin kembali semua hubungan pertemanan lama—yang memang sudah semestinya dikatakan, dan sembari meminta pertolongan kepada teman-teman itu? Tapi di saat bersamaan, seseorang itu juga ingin mengatakan seperti kebanyakan orang—makin ramah cara mengatakannya akan makin membuat laki-laki itu terluka—bahwa usaha yang dilakukan lelaki itu sudah gagal, dan dia mestinya merelakan semua dengan pulang ke kampung halaman, membiarkan dirinya dianggap sebagai bocah pemboros yang akhirnya kembali. Barangkali tidak seorang pun akan mengerti penderitaannya, sebab di mata mereka, kini dia hanyalah bocah tua yang butuh pertolongan dari teman-teman kaya yang lebih memilih bertahan di kampung halaman. Lalu, bagaimana seseorang bisa tega mengutarakan benar maksudnya mengingat seluruh penderitaan yang dia alami? Dan dengan begitu, akan sulit juga membujuknya pulang. Dia terang-terangan mengatakan tentang dirinya yang sudah tidak mengenal lagi kondisi kampung halamannya, memutuskan untuk bertahan di tanah asing, selain karena nasihat-nasihat pahit yang dikatakan teman-temannya, yang kerap membuatnya merasa diasingkan. Namun, jika dia benar-benar menuruti nasihat-nasihat itu, dia akan tertekan di sini. Keadaan tidak mendukungnya untuk bisa bertahan hidup, baik bersama teman atau tanpa teman. Dia akan malu mengetahui dirinya benar-benar tak punya tempat pulang, bukankah hal itu berarti dia lebih baik tetap bertahan di sana, seperti yang dia putuskan? Dengan pertimbangan seperti itu, seseorang itu berpikir, jika dia meminta temannya pulang, dia hanya akan memperburuk nasib temannya di sini.
Dengan pertimbangan itu pula, karena seseorang itu ingin menjaga hubungan dengan bersurat-suratan, dia pikir tak perlu mengirimkan kabar yang sebenarnya yang bisa merusak kedekatan di antara mereka. Hal semacam itu berlangsung lebih dari tiga tahun sejak teman itu pergi dari rumah. Seseorang itu menceritakan hal-hal yang dibuat-buat, tentang kondisi politik di Rusia yang tidak mengijinkan pengusaha kecil keluar dari sana, meski di samping itu, orang-orang Rusia tetap bisa berpergian ke mana saja. Dan itulah tiga tahun yang mengubah George. Sejak ibunya meninggal, kurang lebih dua tahun sebelumnya, George tinggal serumah, berbagi atap dengan ayahnya yang renta. Temannya mengetahui hal itu, dan beberapa kali menyatakan rasa simpati datar melalui surat-suratnya. Bagi temannya, kesedihan yang diceritakan George benar-benar tidak dapat dibayangkan terjadi di negeri asing. Ketika itu George mengambil alih semuanya termasuk urusan perusahaan dengan ambisi dan tekad yang kuat. Barangkali jika ibunya masih hidup, ayahnya tak akan membiarkan keinginan George mengambil alih dan mengembangkan usaha dengan caranya sendiri. Barangkali karena, sejak ibunya meninggal, ayahnya menjadi lebih ceroboh dalam menangani perusahaannya. Barangkali keberuntungan memegang peran yang lebih besar—sesuatu yang mungkin sekali terjadi, karena selama dua tahun itu, perusahaan mereka mengalami peningkatan pesat. Mereka menambah jumlah karyawan dua kali lipat, perputaran uang menjadi lima kali lipat, dan tidak menutup kemungkinan usaha mereka akan terus berkembang di masa yang akan datang.
Temannya, bagaimanapun juga, tidak perlu mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Sebelumnya, barangkali di surat pernyataan bela sungkawa yang terakhir, dia menyarankan George untuk pindah ke Rusia, mengembangkan usaha bermodalkan pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan perusahaan. Hal itu bisa menguntungkan George jika melihat bagaimana perusahaan George kini. Tapi George tidak ingin menulis surat yang berkisah tentang kesuksesan. Dan jika George menuliskan hal itu sekarang, semua terkesan terlambat dan aneh.
Jadi, George memutuskan untuk menulis kepada temannya itu hal-hal yang remeh temeh, barangkali seperti tumpukan kenangan yang muncul ketika seseorang memandangi langit sore di hari minggu yang tenang. Yang dia inginkan adalah tidak merusak gambaran-gambaran diciptakan temannya tentang kota yang lama ditinggalkan, yang barangkali sedang temannya pertimbangkan untuk ditinggali kembali. Maka terjadilah, ketika George menceritakan tiga kali dalam sebuah surat panjang tentang pertunangan antara seorang laki-laki biasa dan perempuan biasa. Dan tidak seperti yang George bayangkan, temannya itu malah penasaran dan tertarik mendengar cerita itu.
George lebih suka menulis kepada temannya kisah itu, daripada mengakui bahwa sebulan lalu dia lah yang bertunangan dengan gadis dari keluarga kaya, Frieda Brandenfeld. George kerap bercerita kepada tunangannya tentang seorang teman dan hubungan yang mereka lakukan dengan bersurat-suratan. “Tak mungkin baginya untuk datang ke pernikahan kita?” tanya gadis itu, “tapi aku punya hak untuk bertemu dengan semua temanmu.” “Aku tidak ingin membuatnya sedih,” George menjawab. “Jangan salah paham. Dia mungkin datang, paling tidak begitulah yang aku harapkan, tapi dia barangkali datang dengan terpaksa, dan merasa terluka, dan iri kepadaku. Dia tentu merasa sedih, apalagi sekarang dia belum mampu mengatasi rasa sedih kembali ke kampung halaman sendiri. Sendiri, bisakah kau mengerti keadaannya?” “Ya, tapi apakah dia tidak bisa memandang pernikahan kita dari sisi lain?” “Bisa saja, tapi aku tidak bisa menjamin hal itu. Bagaimana pun juga, cara pandangnya tidak seperti yang kaubayangkan.” “Jika kau punya teman seperti itu, semestinya kau tidak usah bertunangan saja.” Beberapa saat kemudian, gadis itu, dengan napas tersengal setelah berciuman, mendesak lagi, “Meski begitu, aku tetap merasa kecewa.” Lalu George mulai berpikir untuk mengatakan semua ini sejujur-jujurnya, dia pikir temannya tidak akan merasa terluka. “Memang begitulah aku, dan semestinya begitulah cara dia menerimaku,” pikir George. “Aku tidak perlu menjadi orang lain agar dia merasa nyaman menjalin pertemanan denganku.”
Dan, akhirnya, dia benar-benar mengatakan kepada temannya perihal pertunangan, dalam sebuah surat panjang yang dia tulis di Minggu pagi itu, beginilah kata-katanya, “Berita terbaik disimpan untuk penutup. Aku sudah bertunangan dengan Frieda Bradenfeld, seorang gadis dari keluarga berkecukupan, yang baru datang ke kota ini lama setelah kepergianmu dan mungkin kamu tidak mengenal mereka. Kuharap ada kesempatan lain untuk menceritakan kepadamu tentang tunanganku. Hari ini, kupikir cukup dengan memberitahukan kepadamu bahwa aku sangat merasa beruntung dengan pertunangan ini, dan apabila kau merasa khawatir dengan pertemanan kita ini, satu-satunya yang berubah di antara kita adalah kita akan mempunyai, bukan hanya seorang kawan biasa, melainkan seorang kawan perempuan yang bahagia. Terlebih lagi, tunanganku, yang menitipkan salam hangatnya untukmu, akan segera menulis suratnya sendiri untukmu. Kau akan mendapat seorang teman perempuan yang ramah, sesuatu yang tidak serta-merta mengganggu status lajangmu. Aku tahu ada banyak hal yang menghalangimu untuk pulang dan mengunjungi kami, akan tetapi, bukankah pernikahanku adalah kesempatan yang tepat untuk meruntuhkan tembok penghalang itu? Tapi bagaimana pun juga, lakukanlah apa-apa yang menurutmu baik, tanpa membuat dirimu sendiri tidak nyaman.”
George duduk cukup lama di depan meja tulis dengan surat itu di tangannya, kepalanya menengok ke arah jendela. Dia terhenyak, lalu tersenyum kosong yang dipaksakan ketika menyadari seorang tetangga yang melintas menyapanya dari luar jendela.
Akhirnya dia melipat surat itu dan memasukkannya ke kantong lalu berjalan keluar ruangan, menyusuri lorong kecil menuju ke ruangan ayahnya, yang sudah tidak dia kunjungi selama berbulan-bulan. Tak ada alasan untuk melakukannya, karena dia selalu bertemu dengan ayahnya di tempat kerja dan selalu menikmati makan siang mereka di restoran yang sama. Di sore hari, tentu saja, mereka berdua melakukan urusan masing-masing. Meski seringkali, kecuali saat George dikunjungi temannya, atau sekarang dikunjungi tunangannya, mereka masih melewati sore duduk bersama di ruang tengah, dengan koran masing-masing menutupi wajah mereka.
George terkejut betapa gelapnya kamar ayahnya, bahkan di pagi yang cerah seperti itu. Semacam bayangan yang memanjang dari dinding tinggi yang berada di sisi sungai yang menyebabkan kegelapan itu. Ayahnya sedang duduk membaca koran di dekat jendela di sebuah sudut ruangan yang dihiasi bermacam-macam benda yang mengingatkan pada kesedihan akan kematian ibunya. Koran itu dipegang sedemikian rupa untuk menyesuaikan kemampuan melihatnya yang sudah melemah. Di meja, terlihat makanan untuk sarapan, yang sepertinya belum dia makan sama sekali.
“Ah, George,” kata ayahnya, berdiri dan berjalan ke arah George. Piyama tidurnya yang tidak ditalikan menggantung dan bergerak-gerak seiring dia berjalan. “Ayahku masih seperti raksasa,” pikir George.
Lalu George berkata, “Gelap sekali ruangan ini.”
“Ya, tentu saja gelap,” ayahnya menjawab.
“Dan kau malah menutup jendela?”
“Aku lebih nyaman seperti itu.”
“Padahal di luar cukup hangat,” kata George, seperti hendak mengatakan hal lain, lalu duduk.
Ayahnya membereskan piring tempat sarapan dan meletakkan di lemari makan.
“Aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu,” George melanjutkan, yang diikuti gerakan berjalan yang tanpa daya orang tua itu, “Aku ingin mengirimkan berita tentang pertunanganku ke St. Petersburg.” George sedikit menarik surat dari sakunya tapi segera memasukkannya kembali.
“Ke St. Petersburg?” ayahnya bertanya.
“Kepada temanku,” kata George, mencoba memandang mata ayahnya, “Ayahnya jauh berbeda dengan yang kerap kulihat di tempat kerja,” pikir George. “Sekarang, betapa tegapnya dia duduk dengan tangan terlipat di dada.”
“Oh iya, kepada temanmu,” kata ayahnya, dengan penekanan.
“Begitulah, Yah. Pada mulanya aku ingin menyembunyikan pertunangan ini darinya. Tanpa pertimbangan dan alasan apapun. Tapi kau tahu sendiri, dia orang yang rumit. Aku pikir dia akan bisa memahami pertunanganku ini dan memaafkanku, bahkan jika cara hidupnya yang soliter itu akan membuat semua ini makin sulit, aku tidak peduli, mestinya dia tidak menganggap semua ini masalah personal.”
“Dan sekarang kau memikirkan hal ini dari sudut pandang lain?” tanya ayahnya. Dia menata koran di ambang jendela, dan meletakkan kacamata baca di atasnya.
“Ya, sekarang aku mulai mempertimbangkannya. Jika dia teman baikku, maka aku pikir pertunanganku yang bahagia akan membahagiakannya juga. Itulah mengapa aku tak lagi ragu mengabarkan kepadanya. Tapi sebelum aku mengirim surat kepadanya, aku ingin mengatakan niatku ini kepadamu.”
“George,” kata ayahnya, mulutnya yang tanpa gigi terbuka, “Dengarkan aku! Kau datang kepadaku dengan semua ini, membincangkan semua ini. Tidak ada keraguan bagiku bahwa itu kebanggaan tersendiri. Tapi, itu tidak berarti apa-apa. Lebih parah lagi, jika ternyata kau tidak mengatakan seluruhnya kepadaku. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Sejak kematian ibumu, beberapa hal berjalan tidak semestinya di sini. Barangkali saat-saat untuk membincangkan itu sudah datang, lebih cepat dari yang kita kira. Dalam urusan perusahaan, penjualan yang bagus membuatku tenang. Barangkali tidak ada yang sedang kausembunyikan dariku, sekarang aku tidak menganggap ada yang sedang kaulakukan di belakangku. Aku tidak sekuat dulu, ingatanku sudah menurun, aku tidak bisa jeli dalam melihat segala sesuatu sekarang ini. Pertama-tama, yang terjadi biarlah terjadi, lalu kematian ibumu berimbas lebih parah kepadaku daripada kepadamu. Dan karena kita membahas suratmu itu, aku mohon, George. Jangan memperdaya aku. Ini masalah sepele, tak perlu membahasnya panjang lebar, tapi jangan membohongiku. Apakah kau benar-benar punya teman di St. Petersburg?”
George tertegun malu, “Mari kita lupakan tentang temanku. Bagiku, ribuan teman tetap tak bisa menggantikan seorang ayah. Kau tahu apa yang kupikirkan? Kau tidak serius merawat dirimu sendiri. Tapi usia tetaplah usia. Kau tak tergantikan di perusahaan itu, dan kau sadar benar akan hal itu. Tapi jika urusan perusahaan mulai mengancam kesehatanmu, aku bersumpah, aku akan menutupnya esok hari. Tapi itu tak akan terjadi. Kita harus membicarakan hidupmu dengan cara lain, yang benar-benar berbeda. Di sini, kau duduk dalam gelap saat ruang tengah begitu terang benderang. Kau makan sedikit padahal kau mesti menjaga kesehatanmu. Kau duduk di dekat jendela yang tertutup, padahal udara segar akan membuatmu lebih baik. Tidak seperti itu, Yah. Aku akan membawamu ke dokter, dan kita akan mengikuti anjurannya. Kita akan bertukar ruangan. Kau pindah ke ruangan depan, aku akan menempati ruangan ini. Untukmu, tidak akan ada perubahan. Semua perabotan akan ikut dipindah. Tapi masih ada waktu untuk semua itu, sekarang, aku akan mengantarmu ke ranjang. Kau butuh banyak istirahat. Mari, kubantu kau mengganti pakaianmu. Kau akan lihat, aku bisa melakukannya untukmu. Atau kau ingin pindah ke ruang depan sekarang juga, kau bisa beristirahat di ranjangku. Aku bersedia melakukannya jika kau ingin.”
George berdiri di samping ayahnya, membiarkan rambut putih ayahnya yang acak-acakan terbenam di dadanya.
“George,” kata ayahnya pelan, tanpa bergerak.
George segera berlutut di samping ayahnya. Dia melihat bola mata yang besar di wajah yang lelah ayahnya menatap langsung ke matanya.
“Kau tidak punya teman di St. Petersburg. Selama ini kau terlalu sering membual, dan ketika kau berbicara padaku, kau bahkan tidak bisa mengendalikan sifat burukmu yang satu itu. Jadi bagaimana bisa kau punya teman di sana, aku tidak percaya itu.”
“Berusahalah mengingatnya, Yah,” kata George. Dia mendukung ayahnya dari kursi, dan ketika ayahnya berdiri begitu lemahnya, piyamanya hampir jatuh terlepas. “Sudah hampir tiga tahun sejak temanku itu mengunjungi kita. Aku masih ingat benar ketika kau tidak menghiraukan dia, bahkan ketika dia sedang duduk di ruanganku. Aku bisa mengerti keenggananmu bertemu dengannya. Temanku itu memang terkesan aneh. Tapi kau bahkan sudah berbincang dengannya. Saat itu, aku merasa senang ketika mendapati kau mendengarkan dia, menganggukkan kepalamu, dan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika kau mau mengingatnya, kau mungkin akan ingat. Seperti ketika dia bercerita kepada kita kisah mengagumkan tentang Revolusi Rusia. Misal, ketika dia sedang melakukan perjalanan kerja ke Kiev, di tengah kekacauan di sana, dia melihat pendeta di sebuah balkon menyayatkan tanda salib di telapak tangannya, lalu mengangkat tangan berdarah itu, lalu berteriak-teriak ke kerumunan. Kau bahkan kerap mengulang-ulang cerita itu sampai sekarang.”
Sementara itu, George berhasil membantu ayahnya duduk kembali dan dengan hati-hati melepaskan piyama, yang dia pakai di atas pakaian dalam linen, lalu George melepaskan kaos kaki ayahnya. Melihat seluruh pakaian yang sudah tanggal, yang nampak jelas tidak lagi bersih, George mendesah pada dirinya sendiri bahwa dia sudah menelantarkan ayahnya. Sudah tentu menjadi tanggung jawabnya untuk mengurusi pakaian kotor ayahnya. George belum membicarakan secara terang-terangan kepada tunangannya tentang bagaimana rencananya untuk masa depan ayahnya, karena mereka beranggapan bahwa ayahnya akan memilih hidup sendirian di apartemen tua itu. Namun sekarang dia sudah bulat tekad untuk mengajak ayahnya hidup bersama istrinya nanti. Jika dilihat lebih seksama, sepertinya perhatian yang George sediakan untuk ayahnya sedikit terlambat.
George memapah ayahnya menuju ranjang. Dia mengalami perasaan yang mengerikan ketika dia menyadari, beberapa langkah menuju ranjang, ayahnya melepaskan tangannya dari tangan George hanya untuk memainkan rantai jam yang menggantung di dadanya. George tidak langsung bisa merebahkan ayahnya ke ranjang, dia dengan sikap memegang ayahnya, yang tangannya masih saja memainkan rantai jam.
Segera setelah berhasil merebahkan ayahnya ke ranjang, semua nampak melegakan. George menyelimuti ayahnya, menarik selimut itu bahkan terlalu tinggi, hingga menutupi bahu ayahnya. Ayahnya melihat George dengan pandangan yang tidak menyenangkan.
“Kau masih ingat dia, bukan?” George memberanikan diri bertanya.
“Apa kau sudah benar-benar menutupiku dengan selimut?” tanya ayahnya, memastikan bahwa ujung kakinya benar-benar sudah masuk ke selimut.
“Tidurlah dengan nyaman,” kata George sembari menata ranjang ayahnya agar lebih nyaman lagi.
“Apa kau sudah menutupiku?” Ayahnya bertanya sekali lagi, seperti memaksa George menjawab.
“Tidurlah, selimutnya sudah benar.”
“Tidak!” teriak Ayahnya, memotong jawaban George. Dia melemparkan selimut itu dengan kuatnya sampai melayang, lalu dia berdiri di ranjangnya. Dia menegapkan dirinya dengan satu tangannya yang menyentuh atap. “Kau ingin menutupiku dengan selimut, aku tahu itu, anakku. Tapi aku belum kaututupi dengan kebenaran. Jika ini adalah sisa-sisa tenaga terakhirku, sepertinya pantas kucurahkan kepadamu, bahkan terlalu pantas untukmu. Ya, aku tahu temanmu. Dia sudah kuanggap anak sendiri. Dan karena itulah kau mengkhianatinya bertahun-tahun. Kau pikir selama ini aku tidak menangis untuknya? Itulah alasan mengapa kau mengurung diri di kantor, tidak ada yang boleh mengganggumu, bos sedang sibul. Itulah mengapa kau menuliskan surat-suratmu yang bermuka dua ke Rusia. Tapi sayang sekali, tidak ada yang perlu mengajari seorang ayah untuk mengetahui tingkah polah anaknya. Dan sekarang, ketika kau pikir kau sudah mengelabuinya, kau meletakkan bokongmu di dadanya hingga kaupikir dia tidak bisa bergerak, lalu setelah seperti itu, anakku dengan sikap lelaki sejati mengatakan keputusannya untuk menikah.”
George menatap gemetar ke arah ayahnya. Bayangan temannya di St. Petersburg, yang tiba-tiba dikenal ayahnya sangat baik, tiba-tiba memenuhi kepalanya melebihi biasanya. Dia melihat ekspansinya ke Rusia runtuh. Dia melihat dirinya di ambang pintu menuju kekosongan, kemajuan bisnisnya terampas, berdiri di antara rongsokan, dagangan yang berkeping-keping, tabung gas yang bergelimapangan, hanya berdiri. Mengapa bisa sampai seperti ini!
“Lihatlah aku,” teriak ayahnya, dan George bergegas sadar, terperanjat.
“Karena perempuan itu menaikkan roknya,” ayahnya memulai dengan nada geram, “karena perempuan itu menaikkan roknya seperti ini, angsa menjijikkan,” memeragakan yang dia katakan dengan mengangkat celana pendeknya sedemikian tinggi hingga luka-luka perang di pahanya nampak, “karena perempuan itu menaikkan roknya seperti ini dan seperti itu, kau mulai mengajaknya berbincang, dan beginilah caramu bermesra-mesraan dengannya tanpa merasa terganggu, kau mempermalukan kenangan ibumu, mengkhianati temanmu, dan merebahkan ayahmu di ranjang agar dia tidak bergerak. Tapi dia bisa bergerak, bukan?”
Dan ayah George berdiri tanpa berpegangan, menendangkan kakinya ke arah George. Air mukanya berseri-seri seperti baru saja mendapatkan pencerahan.
George berdiri di pojok kamar, sejauh mungkin dari ayahnya. Sekian lama di sana memutuskan untuk mengamati semua dengan seksama, takut apabila ada serangan mendadak dari atas atau samping yang mengagetkannya. teringat alasan awalnya datang ke ruangan ini, dan mati-matian berusaha melupakannya, seperti berusaha memasukkan benang pendek ke lubang jarum.
“Tapi sekarang temanmu tidak benar-benar dikhianati,” teriak ayahnya, telunjuknya bergerak maju mundur, menekankan maksud perkataannya. “Aku menjadi matanya di sini.”
“Dasar pelawak!” George tidak tahan lagi untuk tidak berkata-kata. Lalu segera menyadari betapa perkataannya memperburuk keadaan dan dia menahan lagi lidahnya. Tapi terlambat, matanya beku, kepedihannya kembali dua kali lipat.
“Ya, memang aku sedang bermain lawakan. Drama. Betapa dunia yang indah. Apalagi penghiburan yang tersisa bagi seorang duda tua sepertiku? Katakan padaku, dan sambil kau menjawabnya, anakku tersayang, apalagi yang tersisa di ruang kerjaku, dipermainkan oleh karyawan yang tidak setia, menjadi renta jiwa dan raga? Dan anakku melenggang bebas mengangkangi dunia, menunggangi perusahaan yang sudah lama aku rintis, menerima semua pujian dengan bangga, dan menelantarkan ayahnya dengan bibir terkatup dan tersenyum layaknya lelaki sejati yang terhormat. Kau pikir aku tidak mencintaimu, aku, seseorang yang membuatmu bisa hidup?”
“Sekarang dia akan terjatuh ke depan,” pikir George. “Bagaimana jika dia terjatuh dan terkapar.” Kata-kata itu berdenging di kepalanya.
Tubuh ayahnya condong ke depan, tapi dia tidak terjatuh. Saat George tidak bergerak mendekat, seperti yang dia harapkan, dia menegakkan lagi tubuhnya.
“Tetaplah di tempatmu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Kau pikir kau masih punya cukup kekuatan untuk memberanikan dirimu sendiri menghampiriku seperti dugaanmu? Bagaimana jika kau salah? Aku masih jauh lebih kuat dari kau. Barangkali apabila aku sendirian, aku sudah akan mundur, tapi ibumu memberikan aku kekuatan untuk bertahan, seperti ketika dia mendorongku untuk menjalin pertemanan dengan temanmu. Dan, aku punya ‘teman’ untukmu di sakuku.”
“Dia bahkan tidak memiliki saku di celana pendeknya.” pikir George, dan seketika itu juga berpikir bahwa ayahnya adalah orang paling konyol sedunia. Pikiran itu hanya selintas saja, sebab di kepalanya pikiran-pikiran lain masih sibuk berlintasan.
“Maka rengkuhlah tangan tunanganmu dan langkahi mayatku. Dan aku akan menghantui hubungan kalian, dan kau tidak akan bisa berbuat apa-apa.”
George menyeringai, dia tidak percaya perkataan ayahnya. Sang ayah mengangguk ke arah sudut di mana George berdiri, menekankan maksud dari perkataannya.
“Sungguh kau membuatku geli hari ini ketika kau datang dan bertanya apakah kau mesti menulis kepada temanmu tentang pertunanganmu. Padahal dia sudah tahu semuanya, bocah dungu, dia sudah tahu semuanya! Aku sudah menulis surat kepadanya, kau lupa mengambil peralatan menulisku. Itulah mengapa dia tidak pernah berkunjung bertahun-tahun, sebab dia sudah tahu ratusan kali dari yang kau tahu. Tangan kirinya meremas suratmu yang tidak pernah dia baca, sedangkan tangan kanannya memegang suratku, ia membacanya.”
Dengan antusias, ayah George mengayunkan tangannya sembari berteriak, “Dia tahu semua ribuan kali lebih banyak.”
“Sepuluh ribu kali!” kata George, perkataannya dimaksudkan untuk mengejek ayahnya, tapi nada bicaranya mengatakan maksudnya lebih jujur dengan bergetar ketakutan.
“Sudah bertahun-tahun aku mengawasimu jika sewaktu-waktu kau akan datang dengan pertanyaan semacam ini. Kau pikir aku peduli dengan hal lain? Kau pikir aku membaca koran? Lihat!” ayahnya melemparkan koran yang entah bagaimana sudah dia bawa ke ranjang ke arah George, sebuah koran lama, yang selama ini tidak pernah diperhatikan George.
“Berapa lama lagi agar kau bisa bersikap dewasa? Ibumu meninggal. Dia tidak bisa menikmati masa-masa yang menyenangkan. Temanmu merana di Rusia, tiga tahun lalu dia sudah cukup merana untuk dibuang, dan seperti keadaanku, kau mengulangi perbuatanmu kepadaku. Kau benar-benar berbakat untuk itu!”
“Jadi selama ini kau berbohong kepadaku,” teriak George.
Dengan nada yang meremehkan, ayahnya berkata dengan tenang dan tegas, “Kiranya kau mengatakan hal semacam itu sejak dulu. Sekarang, perkataanmu terdengar tidak masuk akal.”
Dan dengan suara yang lebih lantang, “Jadi sekarang kau tahu ada dunia di luar dirimu sendiri. Sampai sekarang yang kau pikir hanya dirimu sendiri. Di dalam dirimu, kau hanyalah bocah lugu, tapi lebih dalam lagi, kau adalah manusia yang jahanam! Dan oleh karena itu, camkan ini: kukutuk kau mati tenggelam!”
George merasa dirinya diburu sesuatu dari ruangan ayahnya. Suara tubuh ayahnya yang jatuh menghempas ranjang dan perkataan ayahnya masih terus mengiang di telinganya. Dia serampangan berlari turun, seperti pesawat yang sedang menukik, mengejutkan pembantu rumah tangga yang datang setiap pagi untuk membersihkan rumah. “Ya, Tuhan!” perempuan itu tersentak, melindungi mukanya dengan kedua tangan. Tapi George tidak memedulikannya, dia melompat ke arah pintu, menggeloyor menyeberang jalanan ke arah sungai. Tangannya memegang erat pagar jembatan seperti seorang laki-laki kelaparan menggenggam makanannya. Lalu dia meloncat, seperti gerakan senam yang mengagumkan yang pernah dilakukan di masa mudanya, yang kala itu membuat orang tuanya bangga. Dia masih berpegangan pada pagar, genggamannya melemah, seketika itu dia melihat rombongan motor melintas yang suaranya akan dengan mudah menenggelamkan suara jatuhnya. Dia berbisik lirih, “Ayah, Ibu, aku selalu mencintai kalian bagaimanapun juga,” dan melepaskan genggamannya.
Pada saat itu, ada yang mengalir begitu derasnya melewati jembatan.
nb : diterjemahkan bebas oleh JMW, dari cerpen The Judgement karya Franz Kafka.
Sumber: Facebook Membaca Karya Franz Kafka
http://www.facebook.com/home.php?ref=tn_tnmn#!/groups/252713648090123/






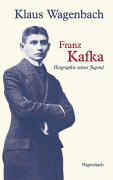

Tidak ada komentar:
Posting Komentar